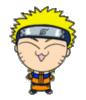Makalah sifat fisika dan kimia golongan III dan IV A
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Unsur-unsur dari golongan IIIA adalah boron (B), aluminium (Al), galium (Ga),
indium(In), dan thalium (Tl). Golongan ini memiliki sifat yang berbeda dengan
golongan IA dan golongan IIA. Dan unsur-unsur pada golongan IVA adalah karbon
(C), silikon (SI), germanium (Ge), timah (Sn), timbal (Pb).
1.2.
RUMUSAN MASALAH
adapun
permasalahan dalam tugas makalah ini adalah:
1. Bagaimanakah
sifat kimia dan fisika golongan IIIA dan golongan IVA?
2. Bagaimanakah
kelimpahannya dialam dari kedua golongan tersebut?
3. Apakah
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimanakah
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari?
5. Bagaimanakah
proses pembuatannya?
1.3.
TUJUAN DAN MANFAAT
1. Agar
siswa dan siswi dapat mengetahui sifat kimia dan sifast kimia golongan IIIA dan
golongan IVA.
2. Agar
siswa-siwi dapat menemikan serta dapat mengetahui bentuk zat kimia dari golongan golongan IIIA dan golongan IVA.
3. Agar
siswa dan siswi dapat mengetahui manfaat golongan IIIA dan golongan IVA dalam
kehidupan sehari-hari.
4. Agar
siswa dan siswi dapat mengetahui proses pembuatannya.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1. SIFAT KIMIA
DAN FISIKA
a. SIFAT
FISIKA GOLONGAN IIIA
Tabel sifat fisika golongan IIIA
Lambing unsur
|
B
|
Al
|
Ge
|
In
|
Ti
|
Nomor atom
Jari –jari atom (A0)
Jari –jari ion (A0)
Titik Leleh (0K)
Titik Didih (0K)
|
5
0,80
-
2300
4200
|
13
1,25
0,45
923
2720
|
31
1,24
0,60
303
2510
|
49
1,50
0,80
429
2320
|
81
1,55
0,95
577
1740
|
Tabel diatas menunjukkan ringkasan beberapa
sifat penting dari unsur-unsur golongan IIIA. Fakta yang terpenting pada tabel
diatas adalah tingginya titik leleh Boron dan titik leleh Galium yang relatif
rendah; peningkatan yang signifikan pada potensial reduksi dari atas ke bawah
dalam satu golongan; tingginya energi ionisasi dari golongan nonlogam (boron)
dan besarnya peningkatan kepadatan dari atas ke bawah dalam satu golongan.
b.
SIFAT
FISIKA GOLONGAN IVA
Karbon dan silikon
termasuk unsur golongan IVA. Anggota unsur golongan IVA lainnya adalah
germanium (Ge), timah (Sn), plumbum (Pb). Di sini kita hanya akan mempelajari
sifat unsur karbon dan silikon. Perhatikan sifat fisika karbon dan silikon
berikut ini:
Sifat
|
C
|
Si
|
|||
Nomor atom
Titik leleh (K)
Titik didih (K)
|
6
3.510
3.930
|
14
1.412
2.680
|
c. SIFAT
KIMIA GOLONGAN IIIA
Pada makalah ini
sifat kimia yang kita pelajari hanya kimia boron dan aluminium.
1. Boron
Boron adalah unsur yang
tidak reaktif pada suhu biasa. Bila bereaksi, tidak ada kecenderungan dari atom
unsure boron untuk kehilangan elektron-elektron terluar dan membentuk kation
sederhana yaitu B3+.
Adapun reaksi pada boron adalah sebagai berikut:
a)
Reaksi
dengan halogen
Boron bereaksi dengan halogen secara umum, bahkan sampai
terbakar dalam gas fluor.
2 B + 3 X2 2 BX3 X = atom halogen
b) Membentuk asam oksi
ika dipanaskan dalam
udara, unsur boron bereaksi dengan oksigen dalam pembakaran yang sangat
eksotermik untuk membentuk oksida B2O3. Oksida ini
bersifat asam. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut.
B2O3(s)
+ 3 H2O(l)
2 H3BO3(l)
asam borat
c)
Semua
boron yang larut membentuk larutan yang bersifat basa bila dilarutkan dalam
air, di mana ion. BO32- bertindak sebagai basa dengan
menghilangkan proton dari air.
BO3 2 ¯(aq) + H2O(l)
HBO3¯(aq) + OH¯(aq)
d)
Boron
membentuk molekul-molekul ion raksasa dengan atom oksigen menempati kedudukan
yang berselang-seling dengan reaksi seperti berikut.
|
– B – O – B – O – B – O
|
|
2.
Sifat
Kimia Unsur Aluminium
Sejumlah garam aluminium
seperti halnya logam golongan IIIA mengkristal dalam larutannya sebagai hidrat.
Misal senyawa AlX3.6H2O (di mana X = Cl–, Br,– I–). Aluminium bersifat
amfoter. Perhatikan reaksi berikut.
OH- OH-
(Al(H
O) )3+ (a) Al(OH) (aq) (Al(OH) ) (aq)
H3O+ H3O+
Aluminium dapat berlaku asam atau basa dikarenakan kecenderungan
yang kuat untuk dioksidasi menjadi Al3+. Perhatikan reaksi berikut.
2 Al(s) + 6 H2O(l) → 2 Al(OH)3(aq)
+ 3 H2(g)
Reaksi ini terjadi pada permukaan aluminium yang bersih tetapi
dalam larutan asam atau dengan kehadiran basa kuat, lapisan tipis Al(OH)3 ini
larut dengan reaksi seperti berikut.
2 Al(OH)3(aq) + 2 OH¯(aq) → 2 (Al(OH)4)¯(aq)
d.
SIFAT KIMIA GOLONGAN
IVA
Karbon dan silikon
termasuk unsur golongan IVA. Anggota unsur golongan IVA lainnya adalah
germanium (Ge), timah (Sn), plumbum (Pb). Di sini kita hanya akan mempelajari
sifat unsur
karbon dan silikon.
a.
Sifat
Fisika Karbon dan Silikon
Karbon dan silikon tidak
reaktif pada suhu biasa. Karbon dan silikon membentuk kation sederhana seperti
C4+ dan Si4+.Sifat kimia karbon antara lain sebagai
berikut.
1)
Karbon
bereaksi langsung dengan fluor, dengan reaksi seperti berikut.
C(s) + 2 F2(g)
→ CF4(g)
2)
Karbon
dibakar dalam udara yang terbatas jumlahnya menghasilkan karbon monoksida.
2 C(s) + O2(g)
→ 2 CO(g)
Jika dibakar dalam kelebihan udara, akan terbentuk karbon
dioksida
3)
Membentuk
asam oksi.
Bila karbon dipanaskan
dalam udara, unsur ini bereaksi dengan oksigen membentuk CO2 dan
jika CO2 ini bereaksi dengan air akan membentuk asam karbonat.
CO2(g) + H2O(l) →H4CO3(l)
asam karbonat
4)
Membentuk
garam asam oksi.
Asam karbonat, suatu asam
diprotik yang khas, bereaksi dengan basa menghasilkan karbonat dan bikarbonat,
antara lain seperti berikut.
- K2CO3 = kalium karbonat
- KHCO3
= kalium bikarbonat
- MgCO3 = magnesium karbonat
- Mg(HCO3)2 = magnesium bikarbonat
5)
Kecenderungan
atom karbon membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan rangkap dua dan ikatan
rangkap tiga yang akan membentuk senyawa organik.
Sifat kimia silikon, antara lain seperti berikut.
1.
Silikon
bereaksi dengan halogen, secara umum reaksi yang terjadi dapat dituliskan
seperti berikut.
Si + 2 X2 → SiX4
2.
Bila
silikon dipanaskan dengan oksigen akan membentuk oksida SiO3,
sehingga apabila oksida ini bereaksi dengan air membentuk dua asam yaitu asam
ortosilikat (H4SiO4) dan asam metasilikat H2SiO3. Senyawa
ini tidak larutdalam air tetapi bereaksi dengan basa.
H4SiO4(l)
+ 4 NaOH(l) → Na4SiO4(l) + H2O(l)
3.
Silikon
membentuk garam dari asam oksi, antara lain seperti berikut.
- Na2SiO3
= natrium metasilikat
- Mg2SiO4 = magnesium ortosilikat
- LiAl(SiO3)2 = litium aluminium metasilikat
4. Semua
silikat membentuk larutan yang bersifat basa yang dapat dilarutkan dalam air, dimana
ion SiO32¯ bertindak sebagai basa dengan menghilangkan
proton dari air.
SiO32¯(aq) + H2O(l)
←⎯⎯⎯⎯→ HSiO3(aq)
+ OH¯(aq)
5.
Silikon
membentuk molekul-molekul dan ion-ion raksasa, di mana atom oksigen menempati
kedudukan yang berselang-seling.
2.2.
KELIMPAHANNYA
DIALAM
1.
kelimpahan
golongan IIIA
a.
boron
Boron tidak ditemukan
bebas di alam, melainkan dalamsenyawaan seperti silika, silikat, dan borat.
Senyawaan boron yang utama dan tidak melimpah adalah asam borat (H3BO3)
dan natrium borat terhidrasi atau boraks (Na2B4O7.10 H2O).
b.
aluminium
Unsur yang terpenting pada
golongan IIIA adalah aluminium. Kelimpahan aluminium terdapat dalam berbagai
senyawaan, seperti batu manikam (Al2O3), tanah liat (Al2(SiO3)3),
kriolit (NaF.AlF3), bauksit (Al2O3.2 H2O).
Bauksit merupakan bahan terpenting untuk memperoleh aluminium antara lain
terdapat di Kepulauan Riau, dan Pulau Bintan.
2.
kelimpahan
golongan IVA
Karbon terdapat di alam
dalam keadaan bebas seperti intan dan grafit. Adapun dalam keadaan ikatan
sebagai bahan bakar mineral, antrasit, batu bara, batu bara muda, dan sebagai
minyak tanah, aspal, gas CO2, dan CaCO3. Karbon di alam
juga terdapat sebagai hasil pembuatan arang amorf, misalkan kokas dari
penyulingan kering batu bara, arang kayu dari pembakaran kayu. Karbon amorf
sesungguhnya adalah grafit yang hablur-hablurnya sangat halus.
2.3.
MANFAAT
GOLONGAN IIIA DAN GOLONGAN IVA
a)
Manafaat
golongan IIIA
a.
Unsur
Aluminium
Aluminium digunakan untuk
membuat barang-barang keperluan rumah tangga, misal piring, mangkok, dan
sendok; untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang; sebagai bahan cat
aluminium (serbuk aluminium dengan minyak cat). Aluminium dapat dicairkan
menjadi lembaran tipis yang dipakai untuk pembungkus cokelat, rokok dan juga
sebagai kaleng minuman bersoda. Daun aluminium atau logam campuran dengan Mg
dipakai sebagai pengisi lamput Blitz, disamping gas oksigen. Selanjutnya
aluminium dipakai untuk membuat beberapa macam logam campur, diantaranya yang
penting ialah duraluminium (paduan 94% aluminium dengan Cu, Mn, Mg), yang
terutama dipakai dalam industri pesawat terbang, dan mobil.
b.
Aluminium
Oksida
Aluminium oksida (Al2O3)
di alam tercampur dengan oksida besi dalam bentuk hablur yang disebut amaril.
Bahan ini sangat keras dan dipakai untuk menggosok besi. Hablur Al2O3
(korundum) juga terdapat dalam bentuk batu permata atau intan berwarna misal
mirah berwana merah (mirah delima), nilam berwarna biru (batu nilam), zamrut
berwarna hijau, ametis berwarna ungu, ratna cempaka berwarna kuning. Batu-batu
ini diperdagangkan dengan nama batu akik, meskipun nama ini tidak tepat karena
yang dimaksudkan dengan akik adalah hablur kwarsa (SiO2).
c.
Senyawa
Asam Borat
Asam borat (H3BO3) banyak dipakai dalam
pabrik kaca dan email. Pada penyamakan kulit digunakan untuk mengikat kapur
dalam kulit.
d.
Garam-Garam
Aluminium Silikat
Beberapa garam aluminium
silikat terdapat dalam tanah liat. Tanah liat merupakan bahan dasar dalam
pembuatan keramik. Ultramarin adalah bahan cat biru yang terdiri dari
Na-Al-silikat dan S. Ultramarin dalam alam terdapat dengan nama lazurit,
dipakai sebagai bahan pembiru pakaian, tekstil, kertas, dan gula.
e.
Senyawa
Natrium Perborat
Natrium perborat NaBO3 . 4 H2O
dengan air menimbulkan oksigen aktif yang digunakan sebagai pemucat dalam
beberapa macam serbuk sabun.
b)
manfaat
golongan IVA
a.
Unsur
Silikon
Oleh karena silikon
bersifat semikonduktor sehingga digunakan sebagai bahan baku pada kalkulator,
transistor, komputer, dan baterai solar.
b.
Pasir
Kwarsa
Pasir Kwarsa (SiO2)
digunakan untuk pembuatan kaca, gelas, porselin, beton. Selain itu SiO2
digunakan untuk menggosok batu kaca, logam-logam untuk pembuatan ampelas dan
untuk pembuatan cat tahan udara.
c.
Kaca Cair
Natrium
Kegunaan kaca cair natrium (Na2SiO3)
adalah untuk bahan campuran sabun cuci dan perekat dalam pembuatan karton.
2.4.
DAMPAK
NEGATIF DARI GOLONGAN IIIA DAN GOLONGAN IVA
Selain bermanfaat ternyata
unsur-unsur yang telah kita pelajari mempunyai dampak negatif.dalam makalah ini
hanya membahas beberapa dampak negativ atom. Adapun dampak negatifnya adalah
seperti berikut.ni
a.
Aluminium
Aluminium dapat merusak
kulit dan dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara bila dipanaskan. Senyawa
aluminium yang berbahaya antara lain aluminium oksida (Al2O3)
yang bereaksi dengan karbon dan berdampak pada pemanasan global. Adapun
reaksinya seperti berikut.
b.
Silikon
Silikon yang dipakai untuk
kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk dan melumpuhkan beberapa
otot wajah. Hal ini karena silikon dapat membentuk gumpalan dan dapat memblokir
aliran darah ke jaringan/organ tubuh.
c.
carbon
Dampak negatif karbon adalah pada senyawa karbon yaitu:
1.
Karbon
dioksida (CO2)
Karbon dioksida
terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil. Adanya pembakaran ini
menyebabkan terjadinya efek rumah kaca.
2.
Cloro
Fluoro Carbon (CFC)
CFC berdampak negatif
terhadap penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca.
3.
Kloroform
(CCl4)
Kloroform menyebabkan
kerusakan hati dan ginjal, dan bersifat racun bila tertelan.
4.
Karbon
disulfida (CS2)
Karbon disulfida
merupakan senyawa mudah terbakar dan bersifat meracuni.
5.
Karbon monoksida
(CO)
Karbon monoksida
biasanya dihasilkan oleh asap kendaraan dan proses industri. Karbon monoksida
lebih mudah mengikat hemoglobin daripada oksigen. Oleh karena itu, darah akan
kekurangan oksigen.
2.5.
PROSES
PEMBUTANNYA
a.
proses
penbuatan aluminium dan boron
1.
Unsur
Aluminium
Aluminium diperoleh dari elektrolisis
bauksit yang dilarutkan dalam kriolit
cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall. Pada proses ini bauksit
ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai
katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam
campuran.
2.
Senyawa
Aluminium Sulfat
Aluminium sulfat (Al2(SO4))
dibuat dari pemanasan tanah liat murni (kaolin) dengan asam sulfat pekat.
3.
Unsur
Boron
Boron dibuat dengan mereduksi boron
oksida B2O3, dengan magnesium atau aluminium. Perhatikan
reaksi berikut.
panas
B2O3(s) + 3 Mg(s) 3 MgO(l) + 2 B(s)
b.
proses
pembuatan silikon
Silikon dapat dibuat dari
reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi, dengan
reaksi seperti berikut.
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
- Unsur-unsur dari logam utama golongan III A adalah : boron ( B), aluminium (Al), galium (Ga), indium ( In), thalium (Tl).
- Unsur-unsur dari logam utama golongan III A umumnya dapat bereaksi dengan udara, air, asam, unsur-unsur halogen membentuk senyawa.
- Unsur-unsur dari logam utama golongan III A di alam tidak ditemukan dalam bentuk unsur melainkan dalam bentuk senyawanya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa proses yang digunakan untuk dapat mengisolasi unsur tersebut dari senyawanya.
- Unsur-unsur dari logam utama golongan III A dan senyawanya memiliki kegunaan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari dan dalam industri.
- Unsur-unsur
pada golongan IVA adalah karbon (C), silikon (SI), germanium (Ge), timah
(Sn), timbal (Pb)DAFTAR PUSTAKASunarya, Yatada dan agus setiabudi, 2009,Mudah dan Aktif Belajar Kimia untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasa Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam,Departemen Pendidikan; Jakarta.Sukmawati dan Wening, 2009, Kimia 3 untuk SMA/MA kelas XII, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta.Pobgajuonto, Teguh dan Tri Rahmidi, 2009, Kimia 3 untuk SMA/MA Kelas XII, Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta.http/google/ logam-utama-golongan-iiia.htmlhttp/google/ GAS MULIA.htm